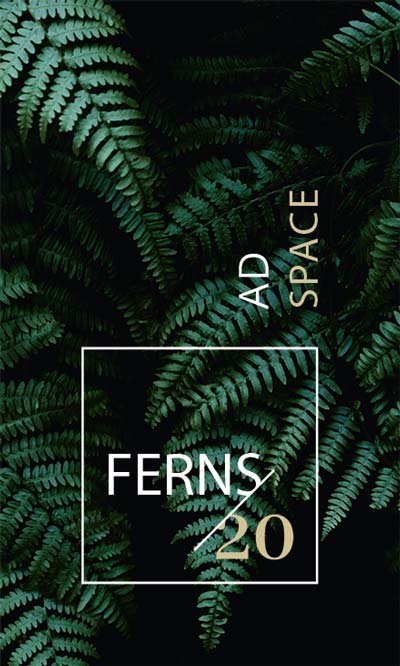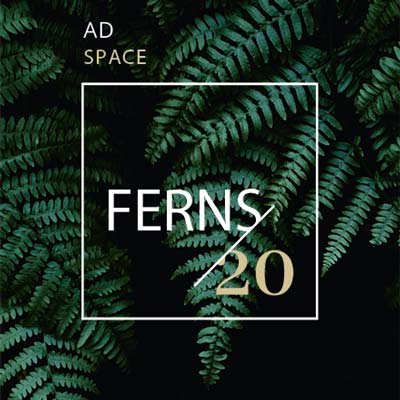“Mereka tidak akan pernah hidup tanpa yam.”
Di Papua Nugini (PNG), yam merupakan sahabat purba. Manusia pertama yang tiba di Pulau Papua membawanya saat mereka bermigrasi dari Asia sekitar 50.000 tahun lalu, dan yam kemudian menjadi bagian dari budaya di sana sejak saat itu
Disebut juga sebagai yam besar, Dioscorea alata, yam tru dalam bahasa Tok Pisin—bahasa kreol Inggris yang digunakan di seluruh PNG—, dan sejumlah nama lain dalam 839 bahasa di negara itu, umbi-umbian tersebut tumbuh cepat di tanah vulkanik. Di Dataran Tinggi Managalas, di kaki bukit berhutan Provinsi Oro, umbi-umbian tersebut disebut ninuri di timur dan manang di barat. Di sana—seperti yang saya pelajari ketika saya mengunjungi dataran tinggi tersebut pada September 2024—budi daya yam merupakan proses yang sangat terkait dengan identitas dan kekuasaan.

“Bagi masyarakat Managalas, menanam kebun yam merupakan proses inisiasi yang diwariskan oleh para tetua,” kata Crispin Burava, seorang petugas pemberdayaan masyarakat untuk Managalas Conservation Foundation (MCF), organisasi lokal yang mengelola Kawasan Konservasi Managalas (MCA) yang luas. “Mereka tidak akan pernah hidup tanpa yam.”
Sebagai makanan pokok yang tahan lama dan bergizi, yam memainkan peran khusus dan krusial dalam perayaan masyarakat dan pertukaran sumber daya. “Ketika menyangkut pesta seremonial, rekonsiliasi konflik, dan kewajiban budaya untuk banyak hal seperti mahar, pasti ada yam,” kata anggota masyarakat Managalas, Bradley Dabadaba.
Praktik ini secara ketat mengatur gender: hanya laki-laki yang diizinkan menanam yam, meskipun perempuan memegang peran penting dalam proses budi daya, seperti menyiangi gulma dan memanen. Laki-laki yang memanen yam yang sangat besar mendapatkan status dalam komunitas mereka. “Saat Anda memanen yam besar di kebun Anda, Anda akan dianggap sebagai orang penting dalam masyarakat,” kata Nehemiah Gaboe, seorang petugas pengembangan bisnis untuk Distrik Ijivitari di provinsi tersebut.
Tidak mengherankan bahwa tanaman ini dikaitkan dengan kejantanan—selain dari tampilannya yang seperti penis sedang ereksi, umbi-umbian ini adalah bukti nyata kemampuan seseorang untuk memberi nafkah. Kapasitas yam untuk memberikan kekuasaan juga diakui lebih dalam. “Di masa lalu, kemampuan seorang pria untuk menanam yam besar diasumsikan tidak hanya terkait dengan kerja keras fisik, tetapi juga kemampuannya untuk memengaruhi dunia nonfisik,” kata ilmuwan Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) dan manajer program PNG Will Unsworth, yang membantu organisasi-organisasi masyarakat di Dataran Tinggi Managalas untuk menyusun rencana pengelolaan bagi kawasan konservasi tersebut.

Community Based Organisation manager, Reckson Kajiaki. Photo by Monica Evans / CIFOR-ICRAF
“Itu adalah cara untuk membuktikan dirinya sebagai orang yang kuat secara fisik dan spiritual dan sebagai orang yang layak didengarkan ketika tiba saatnya bagi klan untuk membuat keputusan penting, seperti tentang tanah, pernikahan, perdagangan, perang, dan lain-lain. Jadi, yam lebih dari sekadar makanan dan ‘nilai’, tetapi melambangkan kepemilikan pengetahuan tradisional, yang memberikan kelayakan untuk dihormati ketika tiba waktunya untuk membuat keputusan.”
Jadi, ketika seorang pria datang ke sebuah pesta atau upacara dengan yam besar, “dia merasa sangat bangga,” kata Reckson Kajiaki, yang mengelola organisasi berbasis masyarakat di salah satu dari sepuluh zona dataran tinggi tersebut
Mendapatkan yam raksasa biasanya tidak terjadi secara kebetulan. “Untuk mencapai ukuran ini, dibutuhkan banyak pekerjaan,” kata Kajiaki. Pertama, orang-orang membersihkan pohon dan semak di area yang ditentukan—untuk menjaga kesuburan tanah, mereka cenderung merotasi tanaman mereka di area-area hutan sekunder yang berbeda, sehingga setiap petak lahan bisa subur kembali sebelum ditanami lagi. Hutan primer biasanya tidak menjadi target, tetapi seiring dengan terus bertambahnya populasi penduduk di Dataran Tinggi Managalas, mungkin ada lebih banyak tekanan untuk melakukannya—salah satu alasan mengapa penyusunan rencana pengelolaan kawasan tersebut menjadi sangat penting.
Menyiangi semak belukar merupakan pekerjaan seluruh anggota keluarga, kata Alking Fufus, yang memimpin Kelompok Teater Kuaefienami Managalas. “Mereka semua bekerja sama—laki-laki menebang, perempuan membersihkan tanah, dan anak-anak memanjat pohon untuk memotong dahan,” katanya. “Jika tidak ada bantuan dari anggota keluarga atau orang lain yang berkepentingan, Anda harus bekerja keras sendiri hingga seluruh kebun selesai.”
Begitu lahannya bersih, para lelaki menggali lubang yang dalam di tanah dengan sekop atau tongkat panjang, mengisinya kembali dengan tanah lunak atau pelepah palem dan menanam benih yam (umbi kecil yang tumbuh menjadi tanaman baru)—yang dipilih secara hati-hati dari tanaman yang tumbuh paling besar dan dipanen pada tahun sebelumnya—di dalam lubang tanah tersebut.
Pemilihan waktu adalah hal yang penting. Yam perlu ditanam menjelang akhir musim kemarau—Agustus hingga November—dan mungkin perlu disiram jika hujan terlambat turun. Panen kemudian dilakukan setelah akhir musim hujan—Maret hingga Juli. Malchus Kajia, yang mengepalai Managalas Conservation Foundation, menjelaskan bagaimana menurut pengetahuan tradisional, yam tumbuh paling baik jika terjadi badai petir besar selama musim hujan setelah benih itu ditanam, karena gemuruh guntur menyebabkan benih yam “melompat keluar dari kulitnya” dan mulai menumbuhkan akar.
Setelah tunas pertama muncul, para lelaki memotong batang-batang untuk menandai tempat mereka. “Kemudian, begitu gulma tumbuh, para perempuan berperan dalam menyiangi kebun itu,” kata Dabadaba. Para lelaki juga mengunjungi kebun secara berkala untuk memastikan yam itu punya ruang untuk tumbuh. “Saat tumbuh, Anda perlu terus menggali tanah di sekitarnya sehingga tanah cukup lunak agar yam dapat tumbuh lebih panjang dan lebih lebar,” ujar Kajiaki.
Ada juga praktik-praktik khusus yang dilakukan di tempat tertentu. Sebagian orang memanen daun tanaman yang tumbuh di sekitar mata air suci dan menaruhnya di sekitar tanaman yam—“itu seperti kekuatan ajaib yang membuat yam itu tumbuh,” kata Kajiaki. Sebagian orang akan merendam kulit pohon lokal dalam air selama beberapa bulan, lalu menyiramkannya ke tanaman tersebut. Sebagian lainnya menggunakan kekuatan pelindung dari jenis akar tertentu: “Sebagian orang datang dan menghancurkan [tanaman yam milik orang lain] agar yam orang lain tidak tumbuh besar, jadi mereka menggunakannya di sana untuk melindungi yam mereka,” kata Fufus.
Sebulan setelah perjalanan saya ke Managalas, saat saya pulang ke rumah di Selandia Baru, sebuah foto muncul di ponsel saya: seorang pria bertopi bisbol dan celana pendek denim berdiri di samping yam terbesar yang pernah saya lihat—tampaknya hampir dua kali lebih besar dari ukuran tubuhnya. Keterangan dari Kajiaki berbunyi sebagai berikut: “Yam ini berasal dari Desa Manusi, digali oleh John Saks, 35 tahun. Ini adalah yam terpanjang yang pernah ada di Yombu: 2,75 meter.” Pria itu tersenyum bangga: ia telah mendapatkan rasa hormat atas jerih payahnya—dan semua orang akan memakan yam itu.

John Saks of Manusi Village holds up his 2.75 metre yam. Photo by Kajiaki
Ini adalah bagian kedua dari seri cerita ini. Baca Bagian 1 di sini untuk melihat seperti apa upacara mas kawin—dengan menara ubi raksasa yang unik.
Untuk informasi lebih lanjut tentang proyek ini, silakan hubungi William Unsworth (CIFOR-ICRAF) di: w.unsworth@cifor-icraf.org
Kami persilahkan Anda untuk berbagi konten dari Berita Hutan, berlaku dalam kebijakan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Peraturan ini mengijinkan Anda mendistribusikan ulang materi dari Kabar Hutan untuk tujuan non-komersial. Sebaliknya, Anda diharuskan memberi kredit kepada Kabar Hutan sesuai dan link ke konten Kabar Hutan yang asli, memberitahu jika dilakukan perubahan, termasuk menyebarluaskan kontribusi Anda dengan lisensi Creative Commons yang sama. Anda harus memberi tahu Kabar Hutan jika Anda mengirim ulang, mencetak ulang atau menggunakan kembali materi kami dengan menghubungi forestsnews@cifor-icraf.org